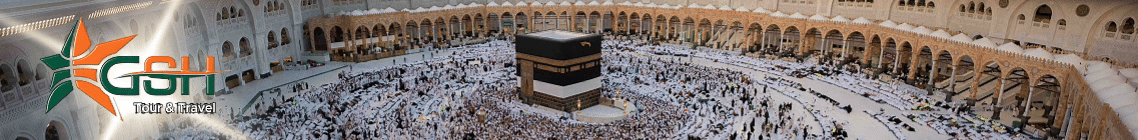INDEKS NEWS.COM –Negara buru-buru membantah. Katanya, tidak benar jagung yang ditanam di Food Estate Kalimantan Tengah berubah menjadi sawit. Dan secara faktual, bantahan itu memang tidak sepenuhnya keliru. Data resmi menunjukkan jagung dan singkong ditanam, sebagian tumbuh, bahkan ada yang dipanen di beberapa titik.
Namun persoalannya bukan sesederhana benar atau salah.
Masalah sesungguhnya adalah negara merasa cukup dengan tidak salah, tanpa memastikan sudah benar.
Food Estate bukan proyek kecil. Ia digadang sebagai tulang punggung kedaulatan pangan nasional. Maka ketika publik melihat hamparan lahan yang tak produktif, ditinggalkan, atau tak jelas kelanjutannya, wajar bila lahir kecurigaan. Terlebih di Kalimantan Tengah—provinsi dengan sejarah panjang alih fungsi lahan pangan menjadi sawit dan tambang.
Benar, sawit tidak serta-merta tumbuh menggantikan jagung di titik Food Estate.
Namun juga benar, yang tumbuh subur justru ketidakpercayaan publik, karena negara gagal membuka keseluruhan data, terutama data kegagalan.
Pemerintah rajin memamerkan panen simbolik, foto tanaman hijau, dan kunjungan pejabat. Tetapi publik tidak pernah diajak melihat gambaran utuh: berapa hektare yang gagal, mati, atau tidak berlanjut. Ketika data kegagalan disembunyikan, ruang kosong itu diisi spekulasi. Dan di situlah bantahan negara kehilangan wibawa.
Lebih dari itu, Food Estate berdiri di wilayah dengan tumpang tindih kepentingan: pangan di satu sisi, ekstraksi di sisi lain. Tanpa pagar kebijakan yang tegas, lahan pangan yang gagal berisiko berubah menjadi “lahan siap pakai” bagi kepentingan nonpangan. Bukan karena konspirasi, melainkan karena kelalaian negara membangun batas etik dan hukum sejak awal.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah pendekatan kekuasaan. Food Estate dirancang secara sentralistis—cepat, luas, dan berorientasi target. Petani lokal kerap diposisikan sebagai pelaksana, bukan pemilik proses. Padahal tanpa keterlibatan dan kepemilikan sosial, tak ada insentif untuk merawat lahan jangka panjang. Yang lahir bukan kedaulatan pangan, melainkan ketergantungan proyek.
Yang paling mengkhawatirkan justru soal ini: ketiadaan exit strategy.
Ketika Food Estate gagal, lahan itu hendak diapakan? Dipulihkan? Dikembalikan ke pangan rakyat? Atau dibiarkan terbuka menunggu kepentingan berikutnya? Tanah tanpa rencana pemulihan adalah undangan sunyi bagi alih fungsi. Bukan karena niat jahat, tetapi karena kebijakan yang ditinggalkan tanpa penutup.
Karena itu, perdebatan “jagung atau sawit” sesungguhnya menyesatkan. Yang lebih penting adalah keberanian negara mengakui keterbatasan, membuka data secara jujur, dan memperbaiki kebijakan sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.
Kedaulatan pangan tidak tumbuh dari konferensi pers dan bantahan cepat. Ia lahir dari transparansi, koreksi kebijakan, dan penghormatan pada pengetahuan lokal. Negara tidak keliru menanam jagung. Yang keliru adalah berharap kedaulatan pangan tumbuh tanpa kejujuran, tanpa evaluasi, dan tanpa mendengar suara tanah itu sendiri. (Yurnaldi, Pemimpin Redaksi)