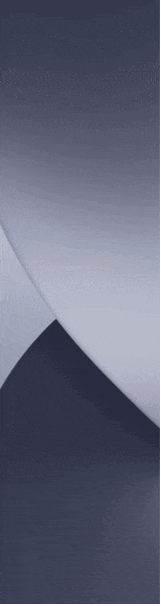Ancaman terhadap kebebasan sipil di Pemilu 2024 dibahas dalam diskusi yang dilaksanakan di Benteng Rotterdam, Jl. Ujung Pandang, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sabtu (11/11/2023).
Diskusi terkait kebebasan sipil di Pemilu 2024 dirangkaikan dengan pemutaran film sekolah rimba, pembacaan puisi dan diskusi.
Diskusi tersebut digagas oleh Amnesty Indonesia kerjasama dengan Kemendikbud. Isu kebebasan sipil memang menguat jelang pesta demokrasi lima tahunan
Pesta demokrasi nyatanya tidak mengindahkan kebebasan bersuara baik di ruang publik maupun di dunia digital. Hal ini tentu bertolak belakang dengan cita-cita bangsa dan demokrasi itu sendiri.
Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi mengatakan salah satu menguatnya kebebasan sipil dapat dilihat dari Undang-undang (UU) ITE.
UU ini dapat mengkriminalisasi masyarakat, organsiasi sipil, maupun jurnalis. Artinya, pihak berwenang dapat dengan mudah menjerat masyarakat yang kritis.
“Misalnya pasal 27 dan 28 itukan yang selama ini mengancam dan dapat menjerat masyarakat Indonesia. Masyarakat sipil yang kritis dengan itu otomatis akan dipidanakan dengan UU itu,” ujarnya.
Kebebasan berekspresi dan berpendapat terancam, apalagi mendekati pemilu. Hal ini menjadi kekhawatiran kelompok organisasi masyarakat sipil.
Ketika masyarakat sipil atau organisasi menyuarakan pendapat atau fakta. Secara individu atau kelompok bisa mendapatkan ancaman pidana atau psikologi melalui media sosial.
“Khawatiran kami di kebebasan berekspresi dan berpendapat, karena jangan sampai nanti ada organisasi kritis atau jurnalis yang niatnya mengedukasi tapi dipidana,” katanya.
“Begitu juga jurnalis ketika dapat temuan dari calon-calon ini niatnya mau mengedukasi tapi ujungnya di pidana,” ujar Didit
Manajer Kampanye dan Media Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri mengatakan serangan dari kebebasan berekspresi terkadang dimulai dari sosial media.
Ketika netizen menyuarakan fakta di sosial media biasanya mendapatkan serangan digital. Hal ini bentuk dan contoh kecil bagaimana kebebasan berpendapat diredam oleh oknum tertentu.
Pengalaman mendapatkan serangan digital harus diusut. Selain itu dampaknya, masyarakat akan takut untuk bersuara di sosial media.
“Apapun bentuk intimidasi terhadap mereka yang berpendapat itu harus di proses karena ibaratnya ada kejadian tapi dibiarkan saja,” katanya.
“Terbayang gak, bagaimana kemudian masyarakat terbiasa mereduksi ekspresinya sendiri jadi penting dan wajib bagi penegak hukum mengusut kasus ini. Apapun yang terkait intimidasi serangan digital fisik itu harus diusut,” terang Anne.
Pimpinan Umum Project Multatuli, Evi Mariani mengatakan melihat tren saat ini serangan digital akan lebih masif.
Ada beberapa faktor, misalnya saja korban serangan digital tidak melaporkan serangan digital tersebut.
Kedua penegak hukum tidak sigap dan persoalan yang berhubungan dengan masyarakat sipil.
Namun sebaliknya jika yang melapor pejabat tertentu penegak hukum bisa dengan cepat menangkapi masyarakat umum.
Sehingga pelaku serangan digital tidak mendapatkan efek jera atau hukuman. Sehingga hal ini akan terus terulang apalagi pada saat Pemilu. Bahkan serangan digital khususnya bagi individu atau organisasi yang membuka fakta sangat rentan diserang.
“Serangan digital yang selama ini sudah terjadi baik ke projects Multatuli, narasi, tempo, ternyata banyak yang tidak dilaporkan juga itu tidak terungkap satu pun, jadi semacam impunitas untuk pelaku serangan digital,” kata Evi.
“Jadi mereka seperti bebas karena tidak ada hukuman, baik yang dilaporkan polisi tidak ada hasilnya. Jadi kalau trennya mereka tidak ada hukuman, logikanya (serangan digital) akan naik,” pungkasnya.