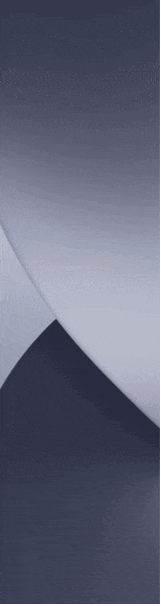Bahder Djohan memenuhi halaman depan hampir seluruh surat kabar di Jakarta dan Padang pada penghabisan Februari 1958. Adalah berita pengunduran dirinya dari jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) yang menjadi buah bibir. Masyarakat tak sangka dia akan bersikap demikian tegas menentang pemerintah pusat.
Duduk perkaranya berpangkal pada ketidaksetujuan Bahder Djohan atas keputusan Presiden Soekarno yang akan menggunakan kekerasan terhadap Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dia berpendapat masalah ini masih bisa diselesaikan lewat perundingan.
Djohan gagal menemui Presiden Sukarno, meski berhasil membicarakannya dengan pejabat-pejabat tinggi negara, terutama yang berkait masalah keamanan seperti Jenderal Abdul Haris Nasution. Sayang, upayanya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan itu berakhir buntu.
Operasi militer terhadap organisasi pimpinan Sjafruddin Prawiranegara yang didirikan 10 Februari 1958 itu bagi Djohan hanya akan berujung pada perang sipil. Artinya, sama saja menciptakan petaka bagi rakyat Indonesia. Padahal baru satu dekade sebelumnya mereka menderita akibat Agresi Militer Belanda I (Juli-Agustus 1947) dan II (Desember 1948).
Kacamata Djohan atas masalah ini, dijabarkan Mardanas Safwan dalam Prof. DR. Bahder Djohan: Karya dan Pengabdiannya, jelas didasarkan kemanusiaan semata. Tak ada pemikiran untung-rugi politik. Keteguhan sikap ini serupa dengan sahabat karibnya, Mohammad Hatta, yang melepas jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada 1956 karena tak setuju dengan sistem Demokrasi Terpimpin.
Bersamaan dengan pengunduran diri itu, Bahder Djohan juga mengajukan pensiun sebagai pegawai negeri. Sejak itulah dia putus hubungan dengan pemerintah. Waktunya kemudian banyak dihabiskan di rumahnya di Jalan Kimia Nomor 9, Jakarta.
Diskriminasi Belanda
Bahder Djohan lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 30 Juli 1902 dari pasangan Mohammad Rapal dan Lisah. Ayah dan ibunya masing-masing berasal dari Bukittinggi dan Kota Padang. Kedudukan sosial sang ayah sebagai seorang jaksa dan bergelar Soetan Boerhanuddin membuat Djohan punya privilese (hak istimewa) atas akses pendidikan.
Anak kelima dari sebelas bersaudara ini mulai menempuh pendidikan pada 1908 di Sekolah Melayu, Padang. Pekerjaan ayahnya sebagai jaksa membuat Bahder Djohan harus berpindah-pindah sekolah. Namun, perpindahan masih di wilayah Sumatera Barat.
Ketika ayahnya ditugaskan di Pariaman, bahder Djohan dimasukkan ke sekolah Eerste Klasse Inlandsche School atau Sekolah Kelas Satu untuk Anak Bumiputra pada 1913 hingga 1915 di Bukittinggi. Pada jenjang pendidikan ini dia pertama kali bertemu dan mengenal Mohammad Hatta.
Kemudian Djohan melanjutkan sekolahnya ke Hollands Inlandsche School (HIS) di Padang hingga lulus pada 1917. Lalu, pendidikannya berlanjut ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Di sekolah ini, dia hanya sampai kelas II karena menerima tawaran untuk bersekolah di School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA) pada 1919.
Karier Djohan di bidang kedokteran dimulai setelah lulus dari STOVIA dan menerima gelar Indische Arts, atau dokter bumiputra, pada 12 November 1927. Dia menyadari ada diskriminasi dalam gelar tersebut. Karena temannya yang seorang Belanda hanya mendapat gelar Arts, tanpa embel-embel.
Diskriminasi dialaminya saat bekerja di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, atau yang kini menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, mulai 1 Desember 1927. Sebagai asisten penyakit dalam, Djohan hanya digaji sebesar 250 gulden. Jumlah itu hanya 50% dari gaji rekan Belanda-nya yang memiliki keahlian dan gelar serupa.
Dia sengit menyuarakan ketidakadilan ini ketika menjadi sekretaris perkumpulan dokter bumiputra yang bernama Vereeniging van Indonesische Geneeskundigen (VIG) selama satu dekade sejak 1929. Baginya ini bukan soal jumlah gaji belaka. Martabatnya sebagai pribadi dan warga bumiputera direndahkan.
“Hal ini terang sekali memperlihatkan bagaimana Pemerintah Kolonial membedakan antara bangsanya sendiri dengan anak jajahannya, meskipun mereka mempunyai pendidikan yang sama,” ujar Djohan dalam otobiografinya, Bahder Djohan Pengabdi Kemanusiaan.
Perdebatan juga terjadi antara dokter bumiputra dengan dokter Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda secara umum terkait akses atas majalah kedokteran. Dunia kedokteran di Hindia Belanda saat itu menerbitkan majalah Geneeskundig Tijdschrift van Nederlandsch Indie. Tetapi hanya dokter bumiputra yang menjadi anggota luar biasa yang bisa berlangganan.
Aturan itu ditentang para dokter bumiputra. Mereka mengancam akan mengundurkan diri dari ikatan majalah kedokteran itu jika peraturan tersebut tak dicabut.
Akhirnya, berkat upaya keras Djohan sebagai sekretaris VIG, Pemerintah Hindia Belanda mencabut aturan diskriminatif ini.
Djohan bersama rekan-rekan dokter bumiputranya juga menentang peraturan yang hanya memperbolehkan bahasa Belanda sebagai bahasa ilmiah di dunia kedokteran Hindia Belanda. Mereka menuntut agar bahasa Indonesia bisa digunakan.
Tuntutan itu pun berhasil setelah bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan dalam dunia kedokteran saat Kongres Perkumpulan Dokter Bumiputra di Solo pada 1939.
Peran Djohan dalam pengembangan bahasa Indonesia di bidang kedokteran berlanjut pada masa penjajahan Jepang. Saat itu Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda, termasuk bagi orang Belanda. Tetapi karena bahasa mereka sulit dipelajari, mau tidak mau Jepang membolehkan penduduk bumiputra memakai dan mengembangkan bahasa Indonesia.
Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia, yang didirikan 20 Oktober 1943, memberi kesempatan tiap disiplin ilmu untuk mengumpulkan istilah Indonesia dalam bidangnya masing-masing. Komisi ini bertugas menentukan terminologi atau istilah-istilah modern dan menyusun tata bahasa normatif dan menentukan kata yang umum bagi bahasa Indonesia.
Para dokter bumiputra memanfaatkan kesempatan ini dengan membentuk Panitia Pembinaan Bahasa Kedokteran Indonesia yang diketuai Aulia dan Bahder Djohan menjabat sebagai sekretaris. Djohan berhasil mengumpulkan sekitar tiga ribu istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia.
Kedudukan Perempuan
Praktik diskriminatif yang inheren dalam kolonialisme membawa Bahder Djohan pada kesadaran politik emansipatif, kendati dirinya seorang dokter. Tak bisa dimungkiri peran tokoh-tokoh dari dunia kedokteran dalam perubahan sosial pada masa itu signifikan, sebut saja Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetomo. Budi Utomo pun didirikan oleh para mahasiswa STOVIA.
Jong Sumatranen Bond (JSB) atau Perkumpulan Pemuda Sumatera menjadi wahana bagi Djohan untuk belajar mengenai kebangsaan sekaligus mengasah kepekaannya atas ketidakadilan. Organisasi ini kemungkinan pertama kali dia kenal saat Nazir Datuk Pamuncak datang ke Padang pada 1918 sebagai utusan JSB yang dibentuk di Jakarta pada 9 Desember 1917.
Pada kesempatan itu, Nazir membentuk pengurus JSB cabang Padang yang diketuai Anas Munaf. Bahder Djohan duduk sebagai sekretaris, dan Mohammad Hatta sebagai bendahara. Sebagai sekretaris, Djohan bertugas surat-menyurat dengan Pengurus Besar JSB di Batavia. Tetapi kemudian dia harus melepas jabatan itu karena berangkat ke Batavia untuk bersekolah di STOVIA pada 1919.
JSB cabang Padang aktif mengadvokasi masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya soal larangan perkawinan perempuan Minang dengan laki-laki Jawa dan kedudukan perempuan secara umum. Misalnya, mereka mendesak Pemerintah Hindia Belanda untuk membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk mengakses pendidikan.
Tak lama sejak tinggal di Batavia, Djohan diutus pengurus JSB untuk mengikuti kongres kedua pergantian Pengurus Besar JSB pada Desember 1919 di Gedung Loge yang kini menjadi Gedung Kimia Farma. Djohan, yang saat itu berusia 17 tahun, dipilih anggota kongres sebagai sekretaris Pengurus Besar JSB. Sementara ketuanya adalah Amir, lalu Mohammad Hatta sebagai bendahara.
“Begitulah kami bertiga bekerja sama mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk kepentingan pemuda, dan sudah tentu pula untuk kemajuan rakyat Sumatera,” kata Djohan.
Sejak itu aktivisme Bahder Djohan dalam JSB dan gerakan pemuda secara umum kian dalam. Ketika memasuki tahun 1925, organisasi-organisasi pemuda mengarah kepada gagasan persatuan Indonesia, termasuk JSB yang kala itu dipimpin dirinya. Mereka mengadakan rapat pada 15 November 1925 di Gedung Lux Orientis, Jakarta.
Rapat tersebut akhirnya memutuskan Kongres Pemuda Pertama. Kongres bertujuan mendorong kerja sama di antara berbagai macam organisasi pemuda agar terwujud pokok-pokok persatuan Indonesia. Salah satunya untuk menentukan bahasa persatuan.
Djohan bersama rekannya, Sumarto, dipercaya sebagai wakil ketua panitia Kongres Pemuda Pertama yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini dihadiri wakil organisasi dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Studeerenden Minahasae, dan Pemuda Kaum Theosofi.
Dalam kongres itu, dia menyampaikan pidato sepanjang 10 halaman yang berjudul De Positie van de Nrouw in de Indonesische Samneving (Kedudukan Wanita dalam Masyarakat Indonesia).
Menurut hematnya, persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia sama pentingnya dengan persoalan politik dan ekonomi Indonesia. Setiap nasionalis, menurut Djohan, wajib mendengar suara perempuan. Oleh karena itu, posisi perempuan harus setara dengan laki-laki dalam agenda perjuangan bangsa Indonesia.
Kongres ini terbilang berhasil mendorong persatuan gerakan pemuda. Terbukti Kongres Pemuda Kedua yang digelar dua tahun kemudian, tepatnya 28 Oktober 1928, dapat melahirkan Sumpah Pemuda.
“Kongres Pemuda yang pertama itu baru berhasil menimbulkan kesadaran tentang perlu adanya persatuan di kalangan pemuda, perlu adanya satu bahasa kesatuan, tetapi belum langsung berhasil mewujudkannya,” ujar Djohan.
Sahabat Karib Hatta
Perhatiannya pada persoalan bangsa, juga tak lepas dari persahabatan dengan Mohammad Hatta. Mereka bertemu di usia sekitar sebelas tahun di Eerste Klasse Inlandsche School, Bukittinggi. Djohan menceritakan, dalam memoarnya, keakraban mereka terutama berlangsung ketika sama-sama aktif di JSB dan belajar di Batavia. Djohan belajar kedokteran di STOVIA dan Hatta mendalami ilmu ekonomi di Prins Hendrik School. Mereka punya waktu khusus untuk bertemu rutin.
Dari STOVIA, mereka berjalan kaki menuju sebuah warung di Pasar Baru untuk mengisi perut. Nasi goreng dan sate ayam menjadi menu santap reguler mereka di sana. Tak ketinggalan diselingi minum kopi dan obrolan.
“Setelah perut kami kenyang, barulah pergi ke gedung bioskop di Pasar Baru untuk menonton film yang kami senangi. Selesai nonton, kira-kira pukul 09.00, terasa waktu masih cukup banyak. Kami pergi lagi dengan berjalan kaki mengelilingi Weltevreden (kini daerah Jakarta Pusat) sampai kira-kira pukul 11.00 malam,” begitu ceritanya.
Hatta selalu mengantar Djohan kembali ke STOVIA sebelum dia sendiri pulang ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda. Mereka berjalan melalui wilayah Senen dengan melewati sebuah warung yang kadang-kadang menjadi tempat mampir keduanya untuk minum kopi.
Rutinitas ini tak semata untuk bersenda gurau. Djohan dan Hatta selalu bertukar pikiran tentang berbagai masalah di Hindia Belanda hingga soal kebudayaan Barat dan Timur. Kontan Djohan merasa kesepian ketika teman diskusi itu harus berangkat ke Belanda meneruskan sekolah pada 1921.
“Meskipun demikian, hubungan kami tidak terputus. Sekali-kali kami masih berkirim surat. Aku minta kepada Hatta, jika ada waktu luang supaya menulis artikel tentang ekonomi. Biasanya Hatta mengirim karangannya dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi,” kata Djohan.
Dia mengalihkan kesepian ini dengan usaha-usaha memperkuat JSB. Utamanya adalah berkontak dengan para pelajar dari Sumatra Utara dan Sumatra Selatan agar ruang gerak dari JSB bertambah luas sesuai dengan namanya.
Djohan dan Hatta juga sempat memiliki gagasan untuk menerbitkan majalah berbahasa Melayu yang dinamai ‘Malaya’. Mereka sependapat bahwa bahasa Melayu sudah dipakai banyak suku di Hindia Belanda, sehingga bisa menjadi bahasa komunikasi untuk mempersatukan pemuda.
Pengelolaannya direncanakan dengan berbagi peran di antara mereka. Djohan mengatur urusan redaksi, sedangkan Hatta mengurus pembiayaan penerbitan. Dia mengusulkan majalah itu mula-mula terbit tiga bulan sekali, lalu menjadi satu bulan sekali. Sayang, rencana ini tak pernah terwujud lantaran berbagai hambatan.
Gagasan PMI
Bahder Djohan dalam otobiografinya menceritakan, gagasan membentuk Palang Merah Indonesia (PMI) sudah ada sejak 1938. Adalah dokter Senduk dari Sukabumi yang membicarakan hal ini dengan dirinya. Mereka kemudian menyampaikan gagasan tersebut saat kongres Roode Kruis Afdeeling Indie atau Palang Merah Cabang Hindia pada 1940.
Tetapi Pemerintah Hindia Belanda menolaknya. Syahdan, pejabat Belanda justru membacakan surat dari seorang istri pejabat tinggi mereka yang menyakiti hatinya. Orang pribumi itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perikemanusiaan, demikian bunyi surat itu. Perasaan Djohan merasa sangat tertusuk dengan pernyataan ini.
“Betapa pedihnya jawaban yang diberikan oleh orang Belanda terhadap maksud baik orang Indonesia,” ujar Djohan.
Akhirnya, PMI baru berhasil dibentuk satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada 17 September 1945. Organisasi ini dibentuk melalui panitia yang diperintah langsung Menteri Kesehatan RI, Boentaran Martoatmodjo.
Panitia itu terdiri dari lima orang, yaitu Raden Mochtar sebagai ketua, Bahder Djohan sebagai sekretaris, dan tiga orang anggotanya adalah Marzoeki, Djoehana, dan Sitanala. Kemudian Djohan ditunjuk sebagai sekretaris PMI yang dipimpin langsung sahabat karibnya sendiri, Mohammad Hatta, yang kala itu adalah Wakil Presiden RI.
Hanya dua hari berselang PMI didirikan, 19 September 1945, rapat raksasa digelar di Lapangan Ikada Jakarta. Djohan berinisiatif membangun pos PMI. Tujuannya untuk memberi pertolongan jika jatuh korban akibat bentrok dengan tentara Jepang. Diketahui saat itu Jepang mendapat instruksi untuk mengamankan situasi oleh sekutu yang akan datang ke Indonesia. Mereka mendirikan pos-pos pertolongan pertama di belakang pohon-pohon dekat lapangan yang penuh sesak dengan manusia.
Keberadaan PMI menjadi sangat vital dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terhadap ancaman penjajahan kembali Belanda. Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer I pada Juli hingga Agustus 1947, Kantor PMI Jakarta diduduki. Djohan pun terpaksa memindahkan kantor tersebut ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Kebetulan saat itu dia pimpinan rumah sakit itu.
Kemudian pada Agresi Militer II, Desember 1948, Belanda berhasil menduduki seluruh Jakarta, termasuk RSUP. Beruntung peralatan, obat-obatan, dan pasien sudah dipindahkan Djohan bersama rekan-rekannya ke rumah Djohan di Jalan Kimia Nomor 9, sebelum jam malam berlaku mulai pukul 00.00.
Situasi berangsur membaik memasuki dekade 1950. Perang tak lagi berkecamuk. Bahder Djohan kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada 6 September 1950. Dia berkantor di kementerian itu hingga 1953. Pada tahun berikutnya, Djohan diangkat menjadi Rektor Universitas Indonesia.
(Wandha Nur Hidayat)
Telah terbit sebelumnya di validnews.id dengan judul “Bahder Johan dan Komitmen Kemanusiaan”